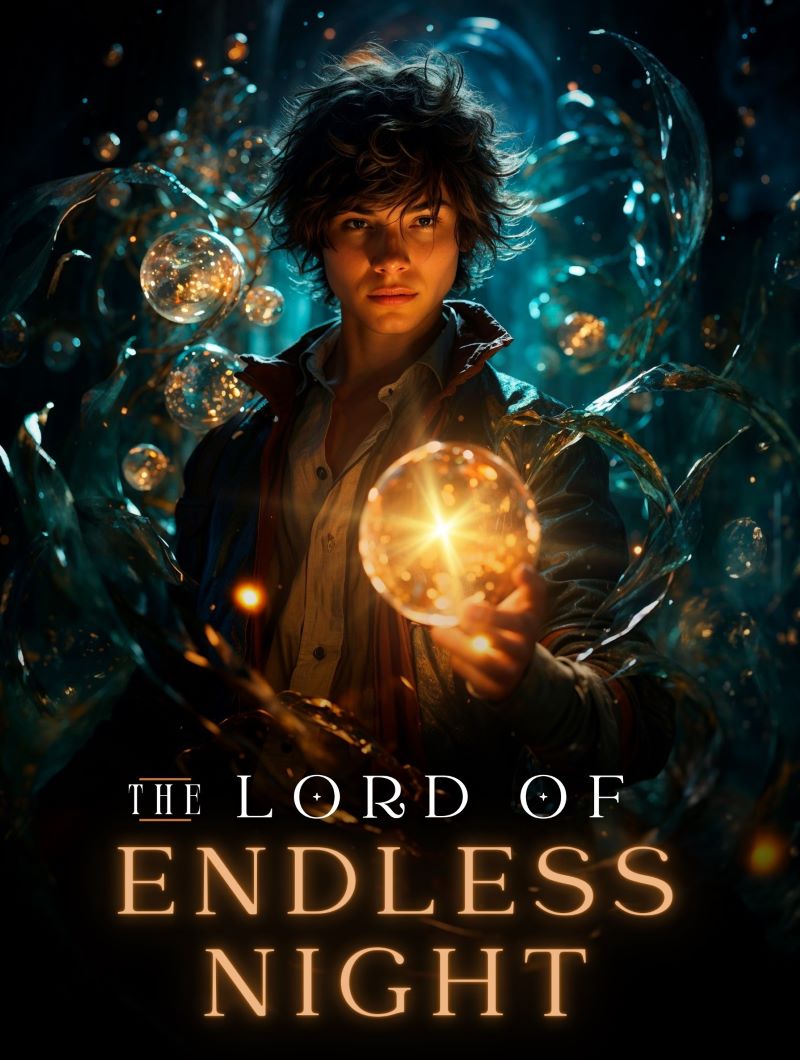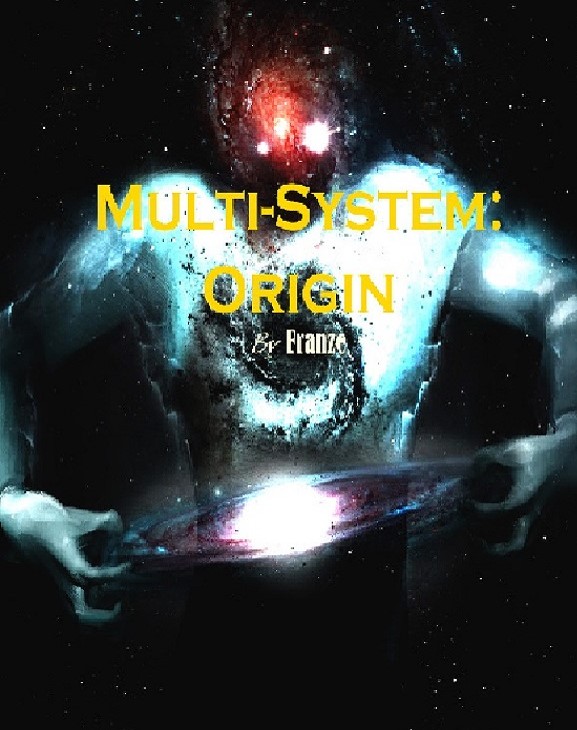Dunia telah dilahirkan kembali.
Menara Katalis menghilang dari keberadaan—bukan hancur, tapi menyatu sempurna dengan aliran waktu, menjadi bagian dari fondasi realitas baru. Celah-celah dimensi telah tertutup. Warna langit menjadi lebih jernih dari yang pernah terlihat sebelumnya. Burung-burung terbang bebas, dan sihir tak lagi meledak liar, melainkan mengalir seperti arus tenang di sungai.
Namun bagi Silvia Akane, dunia ini terasa… terlalu sunyi.
Ia berdiri di lereng bukit, jubahnya tertiup lembut oleh angin musim sihir. Di bawahnya terhampar desa baru yang sedang dibangun oleh para penyihir dan penduduk yang selamat. Sebuah dunia pasca-kejatuhan, penuh harapan dan mimpi. Tapi di dalam dadanya, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan.
“Dulu, kau selalu berjalan tepat di belakangku, Haruto…” bisiknya, menatap langit senja. “Sekarang… bahkan bayanganmu pun tak tersisa.”
Ayase Akane datang menghampiri, membawa dua cangkir teh sihir hangat. Ia tak berkata apa-apa, hanya duduk di samping Silvia, lalu menyerahkan salah satu cangkir padanya.
“Terima kasih,” ujar Silvia lirih, menerima cangkir itu.
Mereka berdua duduk dalam diam cukup lama, hanya ditemani suara dedaunan yang bergesek dan api unggun kecil yang menyala di dekat kaki mereka.
“Kadang… aku bertanya-tanya,” Ayase akhirnya bicara. “Apa yang sebenarnya tersisa dari Haruto? Apakah dia masih hidup? Atau sudah menjadi bagian dari waktu selamanya?”
Silvia tak menjawab segera. Ia menatap ke arah horizon, di mana cahaya sihir dari bintang pertama malam itu mulai menyala.
“Caelus pernah bilang… inti Menara menyatu dengan waktu dan eksistensi. Jika Haruto benar-benar menjadi satu dengan sistem itu, maka dia ada… di setiap detik, setiap helaan napas dunia ini.”
Ayase menatap api. “Jadi… ketika angin bertiup, ketika waktu berjalan tenang seperti ini… itu juga dia?”
Silvia mengangguk pelan. “Ya. Aku ingin percaya begitu.”
Mereka berbicara tentang kenangan kecil—tawa Haruto, cara canggungnya bertanya soal sihir, bahkan keluhan kecilnya tentang makanan di dunia ini. Setiap percakapan adalah upaya menambal luka yang tak terlihat, luka yang meninggalkan bekas jauh lebih dalam dari sihir mana pun.
Setelah beberapa saat, Silvia membuka jurnal sihirnya. Di dalamnya, muncul coretan baru yang tak pernah ia tulis: simbol cahaya yang membentuk lingkaran waktu, dan tulisan halus seperti ditorehkan oleh arus sihir itu sendiri.
“Jika kalian mengingatku… maka aku tak pernah benar-benar pergi.”
Tangan Silvia bergetar.
Ayase melihatnya, dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, ia tersenyum.
“Dia benar-benar ada di mana-mana.”
Silvia menutup jurnalnya perlahan. “Kita harus melangkah maju.”
Ayase mengangguk. “Ada desa-desa yang butuh perlindungan. Distorsi kecil masih muncul. Dunia ini belum sepenuhnya stabil.”
“Kita akan menjaganya,” ucap Silvia tegas. “Bukan hanya sebagai penyihir. Tapi sebagai penjaga harapan. Haruto telah membayar masa depan ini dengan dirinya sendiri. Aku tidak akan menyia-nyiakannya.”
Malam pun turun. Bintang-bintang mulai bermunculan satu per satu, seperti lentera yang bergantung di langit waktu.
Keduanya berdiri, berjalan perlahan menuruni bukit, menyatu dalam cahaya malam. Di langit, satu bintang bersinar sedikit lebih terang dari yang lain—tak berkedip, tak bergerak, seakan mengawasi mereka.
Dan di dalam keheningan malam, tanpa suara, suara Haruto seolah berbisik di antara angin:
“Aku akan selalu ada… di setiap langkah kalian.”